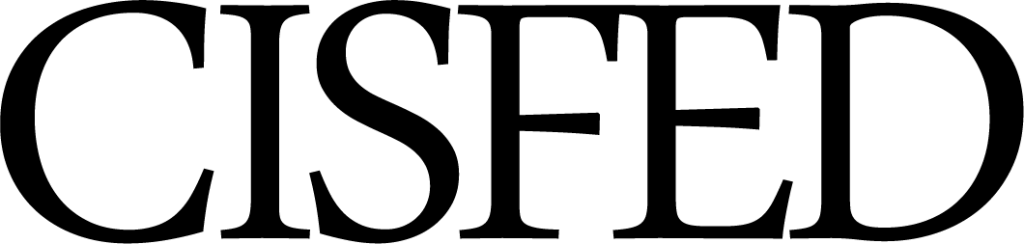Metrotvnews.com, Jakarta: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional mendorong Aji Dedi Mulawarman untuk meluncurkan bukunya yang berjudul ‘Jang Oetama’. Menurut Dedi, inilah momentum yang tepat untuk memperkenalkan sosok Tjokroaminoto, sosok pahlawan nasional yang dikenal sebagai guru bangsa yang berjuang melakukan pembebasan bangsanya dari keserakahan penjajah Belanda pada masa itu.
Tjokroaminoto dijuluki ‘Raja Jawa Tanpa Mahkota’ karena kiprahnya sebagai pemimpin Sarekat Islam (SI) telah menyulut gelombang dukungan masyarakat bumiputera yang kian besar untuk menentang penindasan yang dilakukan pemerintahan di Hindia Belanda.
Menurut Dedi, buku ini menceritakan figur Tjokroaminoto serta pemikiran-pemikirannya hingga menjadi tokoh sentral SI gelar dengan ‘Jang Oetama’. Ia mengisahkan Tjokroaminoto sebagai salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia.
Ia menjelaskan, pada awal abad ke-20, nusantara telah dikoyak kolonialisme Belanda. Namun, tidak ada upaya strategis yang bisa diperbuat masyarakat pribumi agar terlepas dari cengkeraman pemerintahan penjajah. Penjajahan oleh Belanda yang berlangsung hampir lebih dari tiga abad, kala itu membuat mental rakyat Indonesia menjadi rusak.
Masyarakat pribumi mengalami kepasrahan yang akut, karena represi penjajah yang tidak berkesudahan. Mereka menakdirkan dirinya sebagai orang rendahan atau wong kromo yang tak sejajar berhadapan dengan bangsa Belanda. Nahas, kondisi mereka di awal abad ke-20 semakin memburuk karena harta, tanah, keterikatan sosial, fisik dan mentalnya sulit untuk diselamatkan.
Ditambah lagi, kelakuan para priyayi yang kala itu juga ikut-ikutan menindas wong cilik tersebut. Mental ambtenaar alias priyayi yang memihak para penjajah semakin menjadi-jadi, trah kebangsawanan kehilangan kehormatannya karena menjadi cecunguk pelaksana kuasa Ratu Belanda.
“Para saudagar ini mempertahankan zona nyaman, demi self interest atau social interest. Mereka mempertahankan kedudukannya dengan tunduk dan menjilat orang Belanda, sekaligus menginjak wong kromo,” kata penulis Dedi di Jakarta, Rabu (20/5/2015), usai peluncuran buku Jang Oetama: Jejak dan Perjuangan HOS Tjokroaminoto.
Dalam kondisi seperti itu, munculah Tjokroaminoto sebagai seorang keturunan ningrat yang menolak untuk pasrah terhadap ketidakadilan.
Lelaki bernama lengkap Raden Mas Hadji Oemar Said Tjokroaminoto itu lahir di Bakur, Sawahan, Madiun, Jawa Timur, pada 16 Agustus 1882. Tjokro lahir bertepatan dengan meletusnya Gunung Krakatau. Bagi orang Jawa, kelahiran seseorang yang bersamaan dengan meletusnya Gunung Krakatau, dianggap sebagai pertanda kejadian luar biasa. Diramalkan, perjalanan hidup sang anak itu akan berdampak besar bagi masyarakat kelak.
Semasa kecil, Tjokro biasa dipanggil dengan Oemar Said. Dia adalah anak kedua dari 12 bersaudara, dari seorang ayah bernama R.M. Tjokroamiseno, seorang pangreh praja dengan pangkat Wedana di Kleco, Madiun. Sedangkan kakeknya adalah R.M. Adipati Tjokronegoro, yang pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo.
“Berdasarkan silsilah keluarganya, ia memiliki darah kiai dan sekaligus priayi. Buyutnya seorang ulama Kiai Bagoes Kesan Besari, pemilik pondok pesantren di Tegal Sari, Ponorogo,” kata Dedi.
Orangtuanya berharap, suatu saat nanti Tjokro dapat bekerja sebagai pegawai pangreh praja penerus tradisi priayi Jawa. Dengan kata lain, pekerjaan Tjokro tunduk pada sistem pemerintahan dan kekuasaan Belanda. Maka dari itu, Tjokro disekolahkan ke OSVIA (Opleidings School Voor Inlandsche Ambtenaren) atau Sekolah Calon Pegawai Bumiputra, di Magelang.
Tamatan dari OSVIA biasanya akan dipekerjakan sebagai pegawai pangreh praja oleh Belanda. Pekerjaan tersebut mulai dari jabatan magang, juru tulis, mantri polisi, asisten wedana, wedana, sampai kemudian menjadi bupati.
Setelah lulus dari OSVIAS, Tjokro sempat bekerja sebagai juru tulis di Glodog, Purwodadi, di kesatuan pegawai administratif Bumiputra Ngawi. Saat itu juga, Tjokro dinikahkan orangtuanya dengan anak priayi lain, anak dari R.M. Mangoensoemo, Wakil Bupati Ponorogo, yaitu R.A. Soeharsikin. Dari pernikahan dengan Soeharsikin, lima anak Tjokro lahir, yaitu Siti Oetari, Oetarjo alias Anwar, Harsono alias Moestafa Kamil, Siti Islamijah, dan Soejot Ahmad.
“Tiga tahun bekerja sebagai juru tulis tidak membuatnya bermimpi meneruskan tradisi ‘priayi pangreh praja’. Jiwanya mulai berontak, pertanyaan mulai banyak berkembang di kepala Pak Tjokro Muda, mengapa kita orang Jawa harus bekerja sebagai pegawai Belanda? Mengapa Belanda sesukanya memerintah orangorang Jawa? Mengapa di luar keluargaku dan para priayi, yaitu di desa-desa petani itu miskin, melarat, tak berdaya, harus setor kepada Belanda? Kenapa tidak ada itu namanya juru tulis orang Belanda? Kenapa kuli-kuli itu semua orang Jawa dan bukannya Belanda?,” kata Dedi.
Akhirnya pada tahun 1905, Tjokro mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya feodal atau priayi. Perlawanan Tjokro tentu saja membuat gusar keluarga besar priayi, terutama dari ayah mertuanya, R.M. Mangoensoemo, sang Wakil Bupati.
Tjokroaminotopun mengambil tindakan nekat. Dia meninggalkan rumah kediaman mertuanya yang menjadi kediamannya selama ini. Walaupun, ketika itu istrinya sedang mengandung anaknya yang pertama. Dia pergi dari Madiun untuk berkelana mencari jati dirinya, mengaji kitab ke berbagai pondok pesantren. Sampai dia menyendiri atau melakukan i’tikaf di tempat yang tidak diketahui keberadaannya.
Setelah perjalanan itu, Tjokro kembali menjemput istrinya dan mengajaknya ke Semarang untuk hidup yang tidak terikat pada tradisi keluarga priyayi. Tjokro pun bekerja serabutan, berinteraksi dengan wong kromo. Bahkan dia juga menjadi kuli pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Beliau meninggalkan simbol priyayi, pangkat dan zona nyaman, dan memilih menjadi bagian wong kromo,” kata Dedi.
Pengalamannya selama rentang tahun 1905 sampai 1907 itulah yang menempa Tjokro memahami bagaimana kehidupan rakyat kecil, wong cilik, buruh, pekerja kelas bawah yang jauh dari kenyamanan hidup. Kondisi inilah yang menjadi cikal bakal letupan ide gerakan perlawanan Tjokro terhadap Belanda.
Pada tahun 1907, Tjokro pindah ke Surabaya dan melanjutkan sekolah di BAS (Burgelijke Avond School), sekolah Teknik Sipil jurusan Mesin. Dia juga bekerja di perusahaan dagang bernama Kooy & Co untuk membiayai kegiatan sekolahnya.
Setelah lulus, Tjokro sempat bekerja sebagai juru mesin (leerling machinist) selama setahun, dan akhirnya menjadi juru kimia (Chemiker) di sebuah pabrik gula, Rogojampi Surabaya, antara tahun 1911 sampai 1912. Di sela-sela pekerjaannya di pabrik gula, Tjokro rajin menulis, terutama tulisan jurnalistik. Banyak tulisannya bercerita tentang kondisi rakyat yang memprihatinkan akibat eksploitasi perusahaan asing dan pendudukan kolonial Belanda.
Tulisan-tulisan kritis itu kemudian banyak dimuat di surat kabar Suara Surabaya, Oetoesan Hindia, Fajar Asia, Bendera Islam, Soeloeh Hoekoem, dan majalah Al-Jihad. Dari tulisan kritis itu, Tjokro mulai dikenal sebagai tokoh muda pembela rakyat kecil.
Melalui gagasan kritisnya, Tjokro mulai melakukan penyadaran Nusantara melalui Zelfbestuur atau pemerintahan sendiri. Untuk merealisasikan hal itu, Tjokro mendidik tiga orang yang nantinya akan menjadi tokoh nasional, yaitu Soekarno, Hamka dan Kartosoewirjo.
Ketiga murid itu dididik di rumah Peneleh. Rumah yang terletak di di Jalan Peneleh VII No. 29–31 Surabaya tersebutmerupakan pusat dari semua hal yang berkembang dalam Pergerakan Nasional di Indonesia.
Saat tinggal di Rumah Paneleh, Tjokro bekerja sebagai pegawai pabrik dan spimpinan Sarekat Islam. Meskipun sebagai pemimpin SI, tidak banyak pendapatan yang dihasilkannya.
Kebutuhan hidup Tjokro juga didapatkan dari menulis di berbagai surat kabar dan mengelola surat kabar sendiri. Salah satunya adalah surat kabar Oetoesan Hindia serta Berdikari yang dibiayai melalui Koperasi bersama teman-teman seperjuangannya, Koperasi Setia Oesaha.
Rumah Peneleh saat itu bagaikan “Rumah Bernyawa” yang menjadi tempat melakukan aktivitas sehari-hari Tjokro, seperti menerima tamu dari kalangan biasa sampai tokoh-tokoh utama negeri yang nantinya bernama Indonesia. Bahkan rumah itu juga menjadi tempat diskursus ideologi, diskursus masalah kontekstual negeri, dan tempat di mana rencana-rencana besar Sarekat Islam digerakkan oleh Tjokro.
Seperti diketahui, pada awal abad ke-20 terjadi perubahan yang mendasar dari gerakan nasional di Indonesia. Gerakan itu mulai bergeser dari kesadaran yang bersifat lokal di pedesaaan ke kesadaran yang bersifat lintas lokal di perkotaan, meski belum bersifat nasional. Beberapa pergeseran gerakan itu ditandai dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905, Djamiat Khoir pada 1905 dan Boedi Oetomo (BU) pada 1908.
“Setelah itu, terjadi perubahan kesadaran yang lebih bersifat nasional, ketika Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Sarekat Islam di tangan Pak Tjokro. Pergeseran kesadaran itulah yang nantinya menyulut keberanian Pak Tjokro berbasis Islam menyerukan nasionalisme nusantara, bukan lagi lintas lokal atau bahkan lokalitas seperti BU atau spasial seperti SDI Tirtoadisoerjo dan H. Samanhudi,” kata Dedi.
Tjokro adalah satu-satunya orang yang berani secara vokal dan terang-terangan mengatakan Hindia harus membentuk pemerintahan sendiri sejak 1912. Pernyataan tersebut dinyatakan Tjokro pada saat Kongres Nasional Pertama Central Sarekat Islam tahun 1916 di Bandung.
Tjokro memprakarsai penggunaan istilah “kongres nasional” untuk menunjukkan maksud pergerakan SI untuk membantu Hindia lekas mendapatkan pemerintahan sendiri yang berdaulat. Sejak saat itu, Tjokro dikenal sebagai motor penggerak utama nasionalisme Indonesia.
Gerakan politik Tjokro sebagai pemimpin SI berhasil meningkatkan anggota organisasi itu dari 2000 orang per Juni 1912 menjadi 2,5 juta orang, setelah tujuh tahun. Ini merupakan prestasi yang tidak tertandingi organisasi apapaun di zaman itu. Penguatan organisasi dilakukan dengan tahapan melalui Sarekat Islam menuju politik Hijrah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) dan puncaknya Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).
Tidak hanya itu, sejak 1912 Tjokro juga melakukan Gerakan Sosial-Ekonomi melalui koperasi, pendidikan, pertanian, pembelaan terhadap hak-hak kepemilikan, blusukan, dan penyadaran komunitas lewat kebudayaan dan pergerakan organisasi. Untuk pendidikan, Tjokro mengagas Moeslem National Onderwijs sebagai ruh sekolah SI.
Penyebaran ideologi Sosialisme Islam oleh Tjokro juga perlu diapresiasi. Penyebaran secara masif itu begitu fenomenal, karena berhasil melucuti faham komunisme yang menjangkiti anggota SI.
Tjokro juga melakukan gerakan relasional aktif yaitu menyampaikan Mosi Tjokroaminoto di Volksraad (Dewan Daerah) bersama Politieke Concentratie, membentuk gerakan kebudayaan Jawa Dwipa, gerakan Islam melalui Tentara Kanjeng Nabi Muhammad, membidani federasi nasional Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tahun 1927. Di tingkat internasional, Tjokro menjadi ketua Kongres Al Islam pada tahun 1922. Kemudian diundang mengikuti Kongres Umat Islam Sedunia di Mekah pada tahun 1922 bersama KH Mas Mansyur.
(ADM )
Sumber : http://m.metrotvnews.com/read/2015/05/20/398059/mengenal-tjokroaminoto-sosok-pelopor-gerakan-nasional-di-indonesia